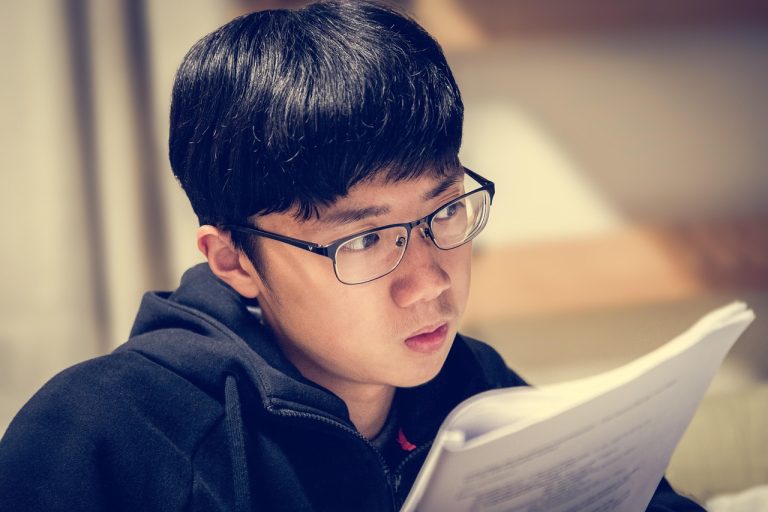Darurat Sampah! Saking daruratnya, topik ini menjadi satu topik paling penting dalam gelaran Munas APEKSI 2025 beberapa waktu lalu di Surabaya. Dan sebelumnya, seorang kepada daerah di sebuah kabupaten melontarkan sayembara bagi jajaran ASN di bawahnya mengenai konsep pengelolaan sampah di kabupaten yang dipimpinnya. Sayembara ini menjanjikan “hadiah” yang sangat menarik: jabatan strategis di Dinas Lingkungan Hidup setempat jika memenuhi syarat administratif. Kebijakan ini sekilas tampak progresif dan mencerminkan semangat meritokrasi sekaligus mempromosikan kreativitas dalam lingkungan birokrasi yang kerap kali dianggap mandeg dan minim inovasi. Tetapi jika dilihat lebih dalam, pendekatan semacam ini justru berpotensi terlalu menyederhanakan (over simplifikasi) terhadap persoalan yang sangat kompleks —persoalan yang tidak bisa diselesaikan hanya melalui sebuah konsep yang jenius hasil sayembara.
Kompleksitas Masalah
Persoalan pengelolaan sampah, termasuk di Indonesia, adalah isu yang sistemik dan multidimensional. Menurut laporan Reformasi Pengelolaan Sampah Nasional yang diterbitkan oleh Bappenas pada tahun 2022, penanganan sampah yang efektif membutuhkan solusi simultan di enam dimensi penting, yakni (1) kualitas perencanaan, (2) data yang aktual dan akurat, (3) kapasitas pemangku kepentingan, (4) kelembagaan yang inklusif, (5) pendanaan yang berkelanjutan, serta (6) pelibatan aktif masyarakat (termasuk sektor informal dan swasta). Dalam hal ini, persoalannya bukanlah karena kurangnya inovasi atau konsep kreatif, tetapi karena tidak adanya ekosistem dan infrastruktur pendukung yang memungkinkan konsep tersebut bisa direalisasikan secara efektif. Inovasi dan inisiatif komunal di Indonesia diakui sangat cemerlang. Namun tidak mampu menyelesaikan masalah sampah karena ekosistem dan lingkungan tidak mendukungnya.
Contoh nyata dari kompleksitas ini dapat dilihat dari proyek pengolahan sampah menjadi energi (Waste to Energy) di Sunter, Jakarta. Proyek yang dicanangkan sejak satu dekade lalu bertujuan untuk menyelesaikan krisis sampah yang dialami Jakarta dengan pendekatan teknologi tinggi. Namun, hingga kini proyek tersebut belum juga terealisasi secara penuh. Proyek ini terjebak dalam berbagai hambatan yang kompleks, termasuk konflik kewenangan antar lembaga, resistensi masyarakat, kajian lingkungan yang kurang komprehensif, ketidakjelasan skema pembiayaan, hingga kelindan kepentingan politik yang menambah rumit kondisinya.
Contoh ini dengan jelas menegaskan bahwa masalah pengelolaan sampah di Indonesia bukan hanya persoalan teknis atau inovasi semata, melainkan juga menyangkut koordinasi lintas sektor dan kemampuan kelembagaan yang kokoh untuk mengimplementasikan solusi secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Kompleksitas Pendanaan
Di samping persoalan kelembagaan, tantangan utama lainnya adalah masalah pendanaan. Di beberapa daerah, sektor pengelolaan sampah adalah salah satu sektor yang dituntut kontribusinya terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah). Selayaknya alokasi APBD harus memadai untuk pengelolaan sampah yang minimal untuk layak dibebani target PAD tersebut. Menurut laporan “Building Robust Waste System Governance and Securing Sufficient Funding” (2021), rata-rata anggaran yang dialokasikan untuk pengelolaan sampah di berbagai daerah di Indonesia hanya sekitar 0,7% dari total APBD, jauh dari angka ideal yang seharusnya mencapai 3-5%. Proporsi pendanaan yang ideal ini ditegaskan kembali oleh Direktur Pengelolaan Sampah KLH Novrizal Tahar beberapa waktu lalu. Minimnya alokasi APBD ini menunjukkan pengelolaan sampah memang belum menjadi prioritas di daerah.
Kenyataan ini menempatkan pengelolaan sampah pada posisi yang sangat rentan karena sebagian besar dana yang tersedia hanya cukup untuk menutupi kebutuhan operasional rutin, seperti gaji petugas kebersihan dan biaya bahan bakar kendaraan operasional, tanpa menyisakan anggaran yang signifikan untuk pengembangan teknologi baru, infrastruktur yang lebih modern dan efektif, ataupun skema pelibatan masyarakat secara intensif.
Situasi ini jelas menunjukkan bahwa konsep inovatif yang tidak didukung oleh anggaran yang memadai hanya akan menjadi harapan kosong. Minimnya dana secara otomatis akan membatasi ruang gerak dan implementasinya, sehingga penyederhanaan solusi pada tataran konsep tanpa menangani akar masalah pendanaan akan menjadi sebuah kesalahan strategis. Lebih kompleks lagi, pendanaan dari APBD tidak bisa dilepaskan dari political will dari penyelenggara pemerintahan. Di sisi lain, kapasitas pengelola dan pengelolaan sampah yang berjalan belum mencukupi untuk bisa mengakses peluang blended finance untuk pengelolaan sampah di luar APBD.
Pengelolaan sampah dalam skala kota tidak hanya membutuhkan gagasan yang brilian dari individu atau komunitas. Namun juga mensyaratkan kemampuan manajerial yang tinggi, keahlian teknis yang matang, kemampuan koordinasi lintas instansi, serta pengalaman nyata di lapangan. Menempatkan seseorang dalam jabatan strategis dan penting ini hanya berdasarkan gagasan tanpa evaluasi menyeluruh tentang kapasitas eksekutif dan pengalaman lapangannya dapat berakibat fatal dan memperparah kondisi yang sudah ada. Salah satu yang wajib dimiliki adalah kemampuan untuk menjembatani integrasi sektor informal dalam rantai pengelolaan sampah ke dalam sistem.
Bahkan rekomendasi Quick Wins Bappenas menyebut bahwa reformasi pengelolaan sampah lebih ditekankan pada penguatan kelembagaan, integrasi data nasional, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan skema pendanaan inovatif dan berkelanjutan. Salah satunya adalah pelembagaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dapat menciptakan fleksibilitas fiskal dalam membiayai operasional pengelolaan sampah.
Meski demikian, inisiatif pemerintah daerah dalam mendorong inovasi di kalangan ASN patut diapresiasi sebagai upaya awal untuk mendorong perubahan dalam pola pikir birokrasi yang tradisional. Namun, apresiasi ini harus diikuti dengan pemahaman mendalam tentang kompleksitas nyata dari persoalan yang dihadapi di lapangan. Akan lebih masuk akal apabila kepala daerah mewajibkan seluruh instansi dalam kewenangannya untuk mempelopori perubahan perilaku aparaturnya dalam menghasilkan sampah.
Kini sudah saatnya dilakukan refleksi serius terhadap strategi yang telah diterapkan pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan sampah ini. Apakah pendekatan yang selama ini digunakan sudah cukup komprehensif dalam memperhitungkan kompleksitas tersebut? Jangan sampai apa yang terlihat sebagai langkah progresif adalah ilusi bahwa solusi instan dapat menyelesaikan persoalan yang sangat kompleks dan interdisipliner ini.
Sekali lagi, pengelolaan sampah yang efektif memerlukan political will yang kuat dengan strategi komprehensif. Lebih dari sekadar konsep out-of-the-box, yang diperlukan adalah komitmen jangka panjang, perencanaan strategis yang matang, dukungan finansial yang memadai, serta kepemimpinan yang kuat dan teruji di lapangan. Dengan pendekatan inilah, kita bisa membongkar ilusi solusi instan dan mulai membangun strategi yang sungguh-sungguh efektif untuk masa depan pengelolaan sampah (perkotaan) Indonesia yang lebih layak. []