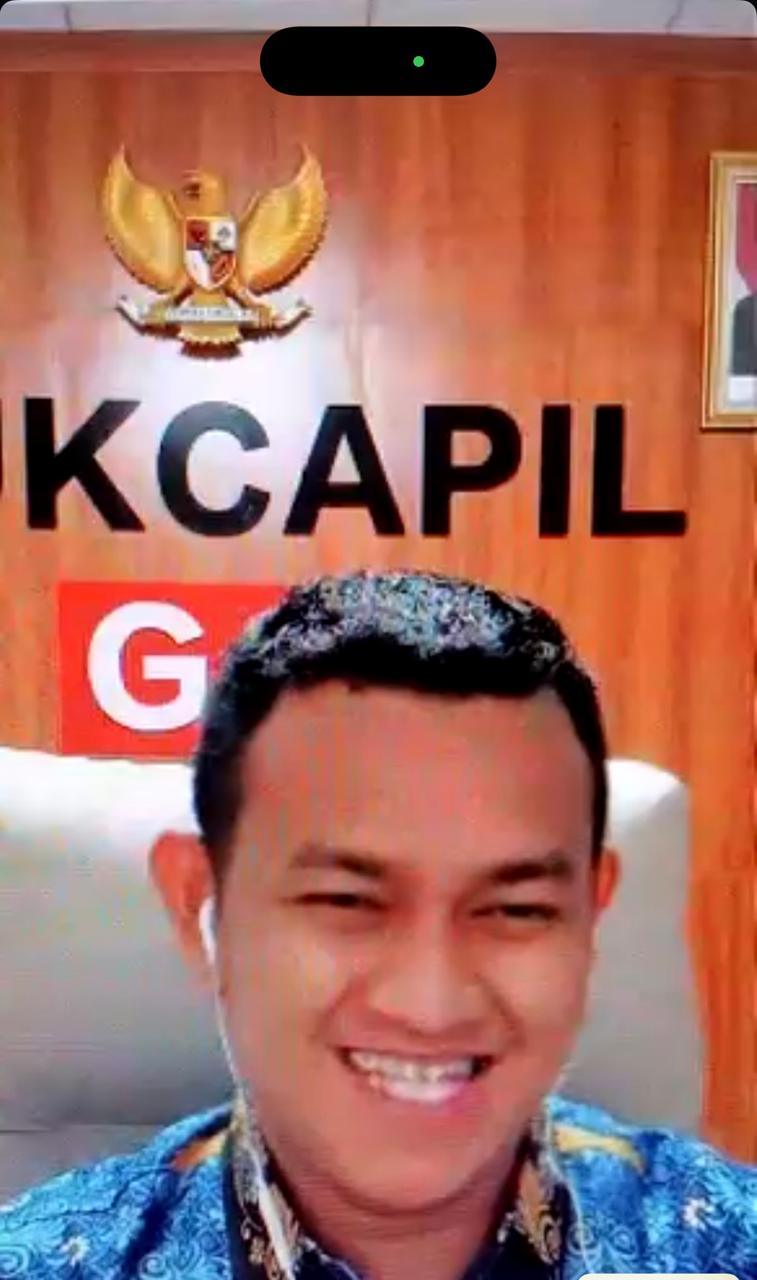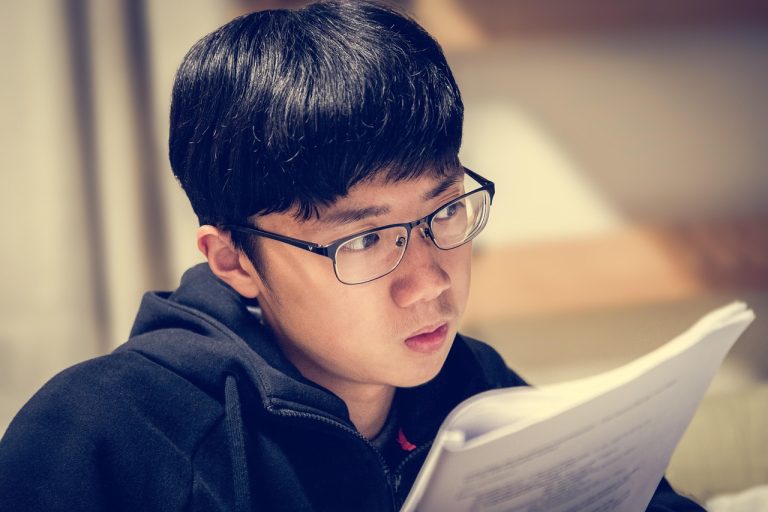Di Surabaya, pekan ini nyaris bergejolak. Bukan karena demonstrasi buruh, bukan pula karena banjir dadakan, melainkan dari satu hal yang kerap dianggap sepele tapi menyentuh urat sosial: parkiran minimarket. Di tangan Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, kebijakan penertiban parkir tiba-tiba berubah menjadi pertarungan tafsir sosial, menyulut reaksi keras dari Forum Solidaritas Madura Indonesia (FSMI).
Semua bermula dari penertiban lahan parkir liar yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya di sejumlah titik ritel modern. Berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2018 dan Perda No. 7 Tahun 2023, area parkir harus memiliki petugas resmi, dengan rompi dan sistem tiket atau struk. Banyak lahan parkir yang tidak memenuhi itu disegel. Tapi masalah muncul bukan pada legalitasnya, melainkan pada siapa yang tersentuh olehnya. Di tengah viralnya video-video parkir di media sosial, muncul narasi yang menyudutkan tukang parkir—dan di Surabaya, seperti di banyak kota lain, tidak bisa dipungkiri bahwa sebagian besar dari mereka berasal dari Madura.
Narasi pun membelok. Dari soal regulasi menjadi urusan identitas. FSMI merasa tersinggung. Mereka menilai langkah Pemkot itu tidak hanya menyingkirkan pekerjaan para jukir, tapi juga memicu sentimen anti-suku tertentu. Ketua FSMI, Baihaqi Akbar, bahkan menyebut akan melumpuhkan Surabaya lewat aksi unjuk rasa besar selama lima hari penuh di depan rumah dinas wali kota.
Namun, cerita ini tak sempat membara. Audiensi dilakukan. Dialog dibuka. Eri Cahyadi akhirnya duduk satu meja dengan perwakilan FSMI. Tidak dalam suasana formal yang mewah, tapi dalam atmosfer krusial yang penuh kehati-hatian. Ia menjelaskan, tak ada maksud mendiskriminasi siapa pun. Penertiban dilakukan demi kepastian hukum dan kenyamanan warga. Bukan hanya untuk penertiban fisik, tapi juga pembenahan sistem agar pajak parkir masuk ke kas daerah dan tak dimakan pungli.
Audiensi itu mengubah arah. FSMI, yang semula siap turun jalan, membatalkan niatnya. Mereka menyampaikan bahwa klarifikasi dari wali kota diterima. Namun mereka tetap meminta agar pemerintah berhati-hati dalam menangani isu yang menyangkut identitas sosial, agar tidak menjadi bahan konsumsi digital yang memicu prasangka dan luka kolektif. Satu kalimat mereka cukup keras: “Tolong, jangan ada lagi konten yang menyudutkan orang Madura.”
Eri sendiri tampak bijak menanggapi gejolak itu. Ia mengatakan, semua warga Surabaya, dari manapun asalnya, adalah bagian dari satu kota yang sama. Ia menyampaikan bahwa dalam masalah ini, bukan soal siapa yang jadi jukir, tapi siapa yang melanggar aturan. Dan siapa pun itu, jika tak sesuai peraturan, harus ditertibkan.
Namun peristiwa ini menunjukkan sesuatu yang lebih besar: betapa cepatnya sebuah kebijakan berubah wajah ketika bertemu dengan tafsir sosial dan distribusi viral. Yang awalnya hanya urusan retribusi, bisa jadi bara identitas. Yang awalnya sekadar “menegakkan perda”, bisa jadi terlihat sebagai “mencabut penghidupan.”
Surabaya yang selama ini tenang-tenang saja dalam hal isu SARA, nyaris terpeleset karena parkiran. Ini ironi sekaligus peringatan. Bahwa di tengah semangat modernisasi kota, ada struktur sosial yang lebih sensitif. Bahwa dalam tata kelola yang serba cepat, empati harus berjalan lebih dulu dari palu penindakan.
Kini, jalanan Surabaya tetap ramai. Minimarket tetap buka. Tukang parkir sebagian kembali berdiri, sebagian menyesuaikan aturan. Tapi aroma konflik itu belum benar-benar hilang. Ia tersimpan dalam ingatan digital, dalam komentar warga, dalam video-video yang menyebar lebih cepat daripada klarifikasi wali kota.
Namun untuk kali ini, Surabaya masih beruntung. Karena yang bicara bukan hanya aturan, tapi juga kesediaan untuk mendengar. Dialog menyelamatkan kota ini dari retak yang lebih dalam. Sebuah parkiran mungkin tak akan pernah terdengar puitis, tapi dalam cerita ini, ia jadi pintu masuk menuju satu hal penting: siapa yang didengar, dan siapa yang dilibatkan dalam membangun kota.